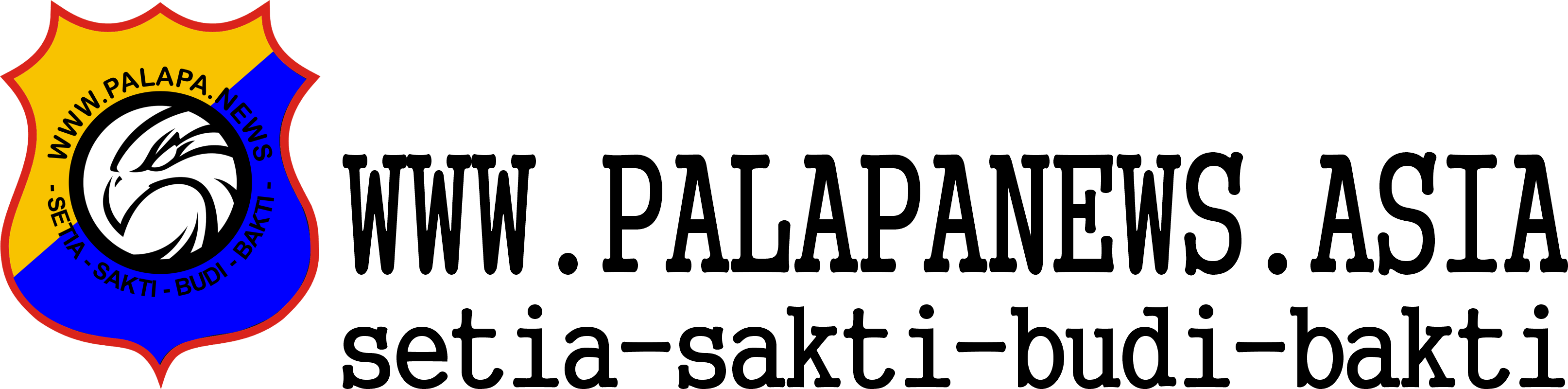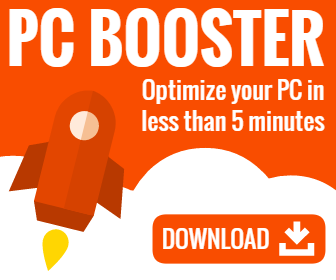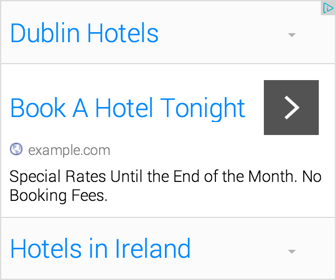Oleh: Prof. Dr. Nandan Limakrisna
Guru Besar Manajemen & Ekonomi, Universitas Persada Indonesia (UPI) Y.A.I
Keyakinan Bank Indonesia (BI) bahwa pertumbuhan kredit perbankan mampu menembus 8% pada akhir 2025 patut diapresiasi sebagai sinyal optimisme di tengah perlambatan ekonomi global. Namun, di balik angka tersebut, ada pertanyaan yang jauh lebih penting untuk dijawab secara jujur: kredit tumbuh ke mana, dan untuk siapa?
Dalam sejarah perekonomian Indonesia, pertumbuhan kredit bukanlah persoalan baru. Yang berulang justru masalah klasiknya: kredit tumbuh, tetapi ekonomi rakyat tetap tertahan. Angka agregat terlihat sehat, sementara di lapangan kita menyaksikan pinjaman online menjamur, kredit nganggur menumpuk, dan UMKM mikro kesulitan mengakses pembiayaan yang wajar. Ini menunjukkan satu hal mendasar—pertumbuhan kredit belum tentu identik dengan pertumbuhan ekonomi riil.
Pertumbuhan kredit 8% akan bermakna jika mengalir ke sektor produktif yang menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan pendapatan berkelanjutan. Namun jika pertumbuhan tersebut terkonsentrasi pada segmen aman, konsumtif, atau sekadar refinancing, maka angka 8% hanya akan menjadi statistik makro yang indah tetapi hampa makna sosial.
Fakta meningkatnya undisbursed loan hingga menembus Rp2.500 triliun seharusnya menjadi alarm. Kredit sudah disetujui, tetapi tidak ditarik. Artinya, sistem keuangan siap menyalurkan dana, sementara dunia usaha menahan diri. Ini bukan soal kurangnya likuiditas, melainkan krisis kepercayaan dan tingginya biaya modal. Dalam kondisi seperti ini, mengejar target angka kredit tanpa membenahi strukturnya justru berisiko menciptakan distorsi baru.
Di sinilah kebijakan moneter dan perbankan perlu melakukan koreksi arah. Fokus tidak cukup pada “berapa persen kredit tumbuh”, tetapi harus bergeser ke bagaimana kredit itu bekerja. Kredit yang sehat adalah kredit yang hidup di transaksi riil, bukan yang mengendap di neraca atau mendorong masyarakat ke jerat pinjol konsumtif.
Jika tujuan akhirnya adalah memperkuat ekonomi nasional dari bawah, maka ada satu instrumen yang selama ini diabaikan secara serius: koperasi desa yang dioperasionalkan dengan Snowball Business Model (SBM). Bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai saluran utama kredit produktif rakyat.
SBM bekerja dengan logika yang berbeda dari kredit perbankan konvensional. Dalam SBM, anggota koperasi adalah sekaligus produsen dan konsumen. Kredit tidak berdiri sendiri, tetapi melekat pada transaksi riil. Uang berputar di dalam komunitas, keuntungan digulung menjadi modal, dan pembiayaan tumbuh dari aktivitas ekonomi nyata. Dengan cara ini, kredit tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi berkualitas dan berdaya tahan.